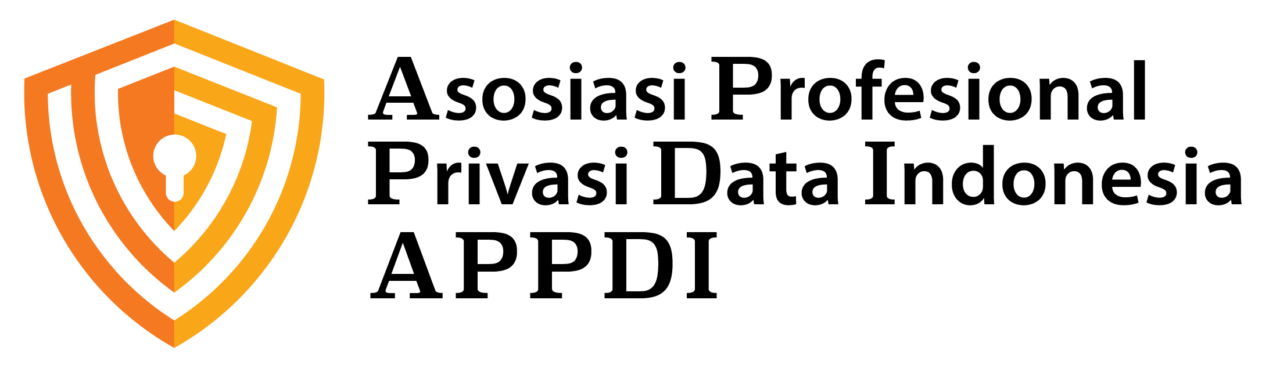kompas.com – Dalam Rapat Paripurna, DPR memutuskan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) diperpanjang (22/6/2021). Ini adalah momen bagi kita untuk menelisik lebih dalam isu dan muatan RUU tersebut. UU ini sangat penting bagi kita, di saat ekonomi digital Indonesia tumbuh eksponensial.
Google dan Temasek (2020) melaporkan, pengguna e-commerce Indonesia meningkat 37 persen karena pandemi, Kenaikan tersebut di atas rata-rata ASEAN.
Sementara pada 2021, Centro Ventures merilis startup Indonesia menerima investasi 70 persen di banding negara lain di ASEAN. Semua itu mengarah pada satu hal: ekonomi digital Indonesia bakal tumbuh pesat. Google memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia bakal mencapai 80 miliar dollar AS pada 2025.
Dalam konteks itu, ada dua UU yang beririsan langsung. Pertama UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kedua, UU PDP. UU yang pertama bakal direvisi seputar isu penyebaran berita bohong.
Sementara terkait RUU PDP, banyak pengamat menilai rancangannya masih terlalu dangkal. Dari jumlah halaman saja, hanya di angka 30-an. Bandingkan dengan UU sejenis di Hong Kong yang mencapai 160-an halaman. Akan jauh sekali jika dibandingkan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa. Belum termasuk beberapa catatan substansial: siapa, apa dan bagaimana serta lembaga yang berwenang, yang dianggap belum tegas.
Catatan penting lainnya, bagaimana UU PDP dapat merespons tantangan dengan lanskap yang lebih dalam: jejak digital (digital footprint) dan pemanfaatannya, yang nyaris belum tersentuh di RUU saat ini termasuk dalam naskah akademiknya.
Dalam RUU itu data dikategorikan dua: umum dan spesifik. Data yang umum seperti nama, jenis kelamin, agama dan seterusnya. Sedangkan yang spesifik seperti data: biometrik, kesehatan, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, keuangan pribadi dan lainnya. Tidak ada pasal yang mengisyaratkan bagaimana raw-data dalam bentuk jejak digital, terlindungi dari penggunaan yang tidak sah, wajar dan adil.
Profil Pengguna
Beberapa waktu terakhir santer masalah kebocoran data: data peserta BPJS dan data pengguna marketplace tertentu. Itu merupakan kasus pelanggaran serta penyalahgunaan yang kasat mata: data bocor. Namun tahun 2014 ada skandal Cambridge Analytica (CA) dengan modus yang lebih shopisticated, canggih! Profil pengguna diekstraksi dari sebuah game tertentu di Facebook dan digunakan untuk memetakan profil pemilih di Pemilu AS. Content-targeted campaign dibuat berdasar profil pengguna sehingga efektif mempengaruhi mereka secara personal.
Ada satu pasal yang nampaknya berusaha memitigasi kasus serupa, “Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling)”, pasal 10. Meski hal itu belum imperatif, sebab di republik yang literasi serta penegakan hukumnya masih lemah ini, hak pengajuan keberatan bisa berhadapan dengan ribuan tembok penghalang. Perintah itu harusnya berbunyi, “Pihak pemroses data dilarang melakukan…”.
Nah, di masa mendatang, bahkan sudah terjadi hari ini, modus canggih seperti itu bakal massif terjadi. Sebagian startup Indonesia sudah investasi besar-besaran ke machine learning, yakni sebuah kecerdasan buatan guna memproses suatu big data.
Apa yang namanya big data jangan dibayangkan sebagai data yang di-entri melalui kolom tertentu, melainkan raw-data dari jejak digital para pengguna. Jejak digital itu bisa berupa: like konten tertentu, komentar, konten posting, jejak pencarian, jejak pembelian, durasi melihat konten dan banyak detail lainnya. Oleh kecerdasan buatan jejak digital ditambang (data mining), diekstraksi dan diolah. Hasilnya, suatu profil pengguna dengan sederet aktivitasnya.
Eropa sangat memahami modus operandi canggih tersebut sehingga mereka mengatur apa yang namanya right to be forgotten, hak untuk dilupakan di GDPR, yakni suatu protokol yang melarang jejak digital pengguna direkam oleh pemroses data. Pengaturan seperti itu sangat relevan juga bagi warga Indonesia, yang 202,6 juta warganya terhubung internet dengan rata-rata penggunaan 5 jam per hari (We are Social, 2021).
Surveillance Capitalism
Nampaknya para perumus RUU harus memahami betul bahwa kita memasuki epos zaman yang berbeda. Shoshana Zuboff, Profesor Harvard, menyebutnya sebagai “the Age of Surveillance Capitalism”, era kapitalisme pengawasan, yang lebih canggih di banding kapitalisme manajerial atau era klasik sebelumnya. Era kapitalisme manajerial ditandai oleh Gm dan Ford. Sedang era kapitalisme pengawasan ditandai oleh Google dan Facebook, kata Zuboff. Mereka memiliki logika kerja yang sama, namun dengan obyek yang berbeda.
Google, masih kata Zuboff, adalah perintis kapitalisme pengawasan. Orang awam mengira Google merupakan perusahaan search engine, namun sesungguhnya adalah perusahaan iklan. Iklan menjadi sumber pendapatan terbesar dari anak perusahan Alphabet ini. Agar iklan bisa efektif, mereka membuat targeted advertising. Agar targeted dan relevan bagi masing-masing pengguna, machine learning bekerja. Jejak digital pengguna diekstraksi dan diolah sedemikian rupa, hasilnya suatu profil pengguna dengan preferensi-preferensinya. Insight itulah yang dijual Google kepada para pengiklan melalui GoogleAds dan produk lainnya.
Zuboff menerangkan cara kerjanya. Bermula dari user behavior yang terakumulasi menjadi big data. Sebagian diolah dan digunakan untuk memperbaiki layanan pencarian, misalnya: ketepatan konten, ketepatan kata, kecepatan dan sebagainya. Sebagian (besar) lainnya, menjadi apa yang ia sebut sebagai “behavioral surplus”. Behavioral surplus ini kemudian diolah lebih dalam menjadi prediction product. Prediksi itulah yang dijual Google, mirip seperti yang dilakukan Cambridge Analytica.
Agar terbayang cara kerjanya begini ceritanya. Anda punya 10 jejak dalam suatu aktivitas pencarian tertentu. Tiga jejak digunakan Google untuk memperbaiki layanan mereka, tujuh sisanya menjadi diambil—Zuboff lebih keras lagi, menyebutnya sebagai dirampas (dispossession)—mereka untuk diolah menjadi prediction product tadi. Bagian yang tujuh itu berarti keluar dari pernyataan persetujuan yang biasanya ada di aplikasi tertentu. Jadi gunung emas baru itu sesungguhnya berasal dari “limbah” yang dihasilkan oleh pengguna. Sayangnya, pengguna tak pernah kebagian bongkahan atau sekedar serpihan emasnya.
Data as Labor
Untuk mempertajam Zuboff, mari kita baca makalah Imanol Arietta Ibarra dkk dari Stanford University, “Should We Treat Data as Labor? Moving Beyond Free”. Ibarra bilang sebenarnya model bisnis “freemium” yang dibarter dengan pertukaran data tidak membangun martabat bagi pengguna (digital dignity). Sebaliknya, menempatkan mereka sebagai sapi perahan yang dieksploitasi terus-menerus secara over-used untuk kepentingan platform belaka. Ibarra menawarkan cara baca baru, bagaimana pengguna dipandang sebagai “pekerja data”, yang karenanya berhak atas pembagian nilai lebih platform.
Mempertegas pandangannya, Ibarra memberikan kerangka analisis yang bagus bagaimana kita seharusnya memandang data: data as capital (DaC) dan data as labor (DaL). Dalam soal kepemilikan, DaC melihat data dimiliki oleh perusahaan, sebab mereka yang mengekstraksi dengan sumberdaya yang dimiliki. Sebaliknya, dalam DaL, data yang dalam bentuk jejak digital itu, dimiliki oleh individu pengguna.
Bagaimana masa depan pekerjaan dengan adanya kecerdasan buatan, perspektif DaC mengusulkan Universal Basic Income (UBI), yang tentu saja anggaran UBI diambil dari pajak, salah satunya pajak dari tech companies. Sedangkan DaL memposisikan lebih bermartabat, bukan skema santunan tanpa kontribusi, sebaliknya melelatakkan “data sebagai pekerjaan”. Karenanya pengguna dibayar dalam proses “memproduksi” data tersebut.
Perspektif Ibarra ini sangat fundamental, sebab mampu menawarkan pandangan bagaimana harga diri individu terbentuk. Ia mengatakan pada DaC, sebab adanya skema UBI, maka lahir budaya “beyond work”. Sedangkan DaL, melahirkan martabat digital, yang memposisikan pengguna sebagai produsen data. Sehingga kontrak sosial yang terjadi berbeda antara DaC, di mana free service for free data, sedangkan pada DaL, terbentuknya suatu data labor market, yang tentu saja lebih adil dan memberi insentif besar bagi pengguna.
Data Work
Contoh operasionalnya mari kita simak pada model bisnis salah satu startup Indonesia, Snapcart.global. Startup ini bergerak di bidang riset pasar, seperti perusahaan riset pasar lainnya, bedanya mereka memanfaatkan big data. Untuk memperoleh data, mereka merilis aplikasi. Cara kerjanya pengguna mengunggah struk belanja yang ditentukan ke aplikasi tersebut. Setiap unggahan struk diberikan imbalan sejumlah koin. Struk dengan nilai transaksi sampai dengan Rp 50.000 akan diberikan 250 koin, Rp 51.000-Rp 100.000 diberikan 500 koin, Rp 101.000 – Rp500.000 dapat1000 koin dan seterusnya. Koin tersebut oleh pengguna dapat ditukarkan menjadi uang.
Dengan machine learning, Snapcart mengolah raw-data struk tadi, hasilnya sebuat data perilaku konsumen di kota/ kabupaten dengan jenis kelamin, usia serta tingkat konsumsi bulanannya. Laporan itu mereka jual dalam bentuk layanan: PASS, OPTI, TASC, ke perusahaan yang membutuhkan, misalnya sektor FMCG, F&B dan sebagainya. Dari sanalah Snapcart memperoleh pendapatan dan membaginya kepada pengguna dalam bentuk koin atas tiap struk belanja yang diunggah.
Dalam kasus Snapcart di atas, peran pengguna terlihat nyata melakukan pekerjaan (mengunggah struk belanja), yang kemudian diberikan imbalan (fee) berupa koin. Hal ini adil bagi kedua pihak, Snapcart dan para pengguna, yang jumlahnya saat ini mencapai 1 juta orang. Dalam perspektif Ibarra, Snapcart berada di sisi DaL. Bayangkan logika itu kita gunakan pada perusahaan iklan Google, di mana kita bekerja ketika melakukan pencarian inkuiri tertentu di mesinnya. Atas pekerjaan itu, Google memperoleh raw-data, diolah dan kemudian dijual ke perusahaan pengiklan. Maka seharusnya, kita sebagai pengguna berhak atas fee, bukan?
Data Labor Union
Dengan melihat perkembangan ekonomi digital yang begitu pesat, UU PDP mendatang harus sangat adaptif dengan itu. Dengan imperatif yang melindungi pemilik data dari penyalahgunaan atau ketidakadilan pihak pemroses data. Google, Facebook, misalnya, tak bisa dilihat sebagai platform mesin pencari dan media sosial belaka, yang memberikan fasilitas gratis kepada pengguna. Mereka harus dilihat sebagai perusahaan iklan yang memonetisasi jejak digital penggunanya untuk kepentingan bisnis. Ada hak ekonomi pengguna (data as labor) yang berhubungan erat dengan mereka.
Dalam fungsi UU sebagai social engineering, UU PDP harus membuka ruang dan mengatur terhadap pola relasi baru seperti di atas. Yang memberikan peluang bagi warga untuk menuntut lebih hak ekonominya kepada platform. Konkretnya, perlu ada pasal yang mengatur pemanfaatan data serta imbal hasil manfaat yang diberikan kepada pengguna. Perlu juga merekognisi prakarsa masyarakat untuk mendirikan perhimpunan atau serikat “pekerja data”.
Contoh nyatanya seperti di Belanda, warga mendirikan Datavakbond atau Data Labor Union pada tahun 2018. Mereka menuntut Google dan Facebook untuk membayar terhadap proses produksi data dari penggunaan platform oleh pengguna selama ini. Bahwa “Tak ada makan siang gratis” juga harus dilempar ke meja para giant tech companies itu. Mereka harus membagi hasilnya ke para pengguna. Kata Ibarra, itu yang akan membuat ketimpangan sosial-ekonomi berkurang. Pengguna Facebook dan Google bersatulah! Anda setuju?
Yoga Sukmana. “RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna” kompas.com. 24 Juni 2021 < https://money.kompas.com/read/2021/06/24/204053826/ruu-perlindungan-data-pribadi-dan-monetisasi-jejak-digital-pengguna?page=all>